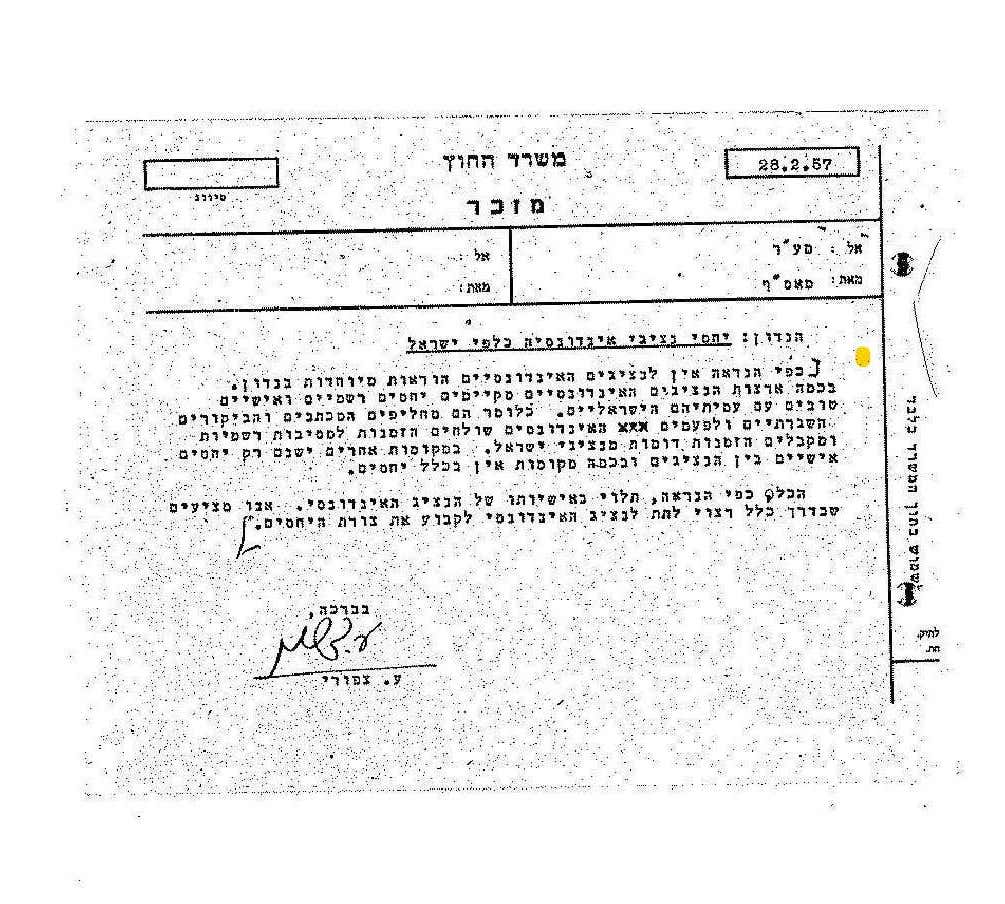Pada bulan November 1957, Kementerian Pertahanan Israel menyiapkan daftar peralatan militer yang siap dijual ke Indonesia, termasuk senjata ringan. Syarat-syarat untuk melakukan penjualan tersebut mendapatkan persetujuan hukum dari Indonesia, bahkan walau kesepakatan itu dilakukan melalui proksi.
Pada Oktober 1958, Israel diminta untuk menjual granat tangan 9mm ke Indonesia. Israel meminta dan menerima persetujuan dari Belanda, yang pada saat itu terlibat dalam persaingan dengan Indonesia untuk menguasai bagian barat Papua.
Dalam sebuah telegram tertanggal 15 April 1958, Shmuel Bendor, perwakilan Israel di Cekoslowakia, melaporkan pertemuan dengan Duta Besar Indonesia di Praha. Menurut Bendor, mitranya dari Indonesia menolak klaim Amerika Serikat dan mengkritik sikapnya terhadap Indonesia.
Baca Juga:Trump Tarik Amerika Keluar dari Perjanjian ‘Mata-Mata’ Open SkiesBeredar Isu ‘Sayonara The Jakarta Post’, Pemimpin Redaksi: Tetap Terbit, Benahi Perusahaan Menuju Era Digital
“Mereka mengatakan bahwa Indonesia sedang menuju Komunisme,” kata diplomat Indonesia tersebut. “Itu adalah kebodohan. Indonesia tidak ingin menjadi bagian dari pihak mana pun, karena kami tidak percaya bahwa dunia terbagi menjadi dua pihak, atau bahwa setiap negara harus memilih salah satu pihak. Inilah yang tidak ingin dipahami oleh Amerika. Misalnya berkaitan dengan senjata—mereka membenci upaya Indonesia untuk memperoleh senjata dari Eropa timur. Indonesia tidak punya pilihan, karena Amerika memaksakan kondisi yang tidak dapat diterima oleh Indonesia (dan ia berbicara tentang bantuan keuangan).”
“Tentara Indonesia yang ‘sengsara’ (istilahnya) harus mendapatkan beberapa senjata baru, karena pemberontak menggunakan senjata baru,” diplomat itu melanjutkan. “Mereka juga mengklaim bahwa Presiden Sukarno bersimpati terhadap komunisme, yang tidak masuk akal. Dia adalah seorang demokrat seutuhnya. Jika ada satu aspek dari ideologinya yang dapat dikritik, itu adalah kecenderungannya untuk menjadi terlalu liberal. Indonesia membutuhkan tangan yang kuat, karena rakyatnya belum siap untuk demokrasi penuh. Berbagai partai politik menempatkan partai politik di atas kepentingan nasional—Ini juga berlaku bagi partai-partai yang berada dalam koalisi pemerintahan—dan ini merusak stabilitas pemerintah. Sukarno tahu ini, tetapi pandangan dunia liberal-nya mencegah dia menggunakan tangan yang kuat untuk menangani masalah ini.”